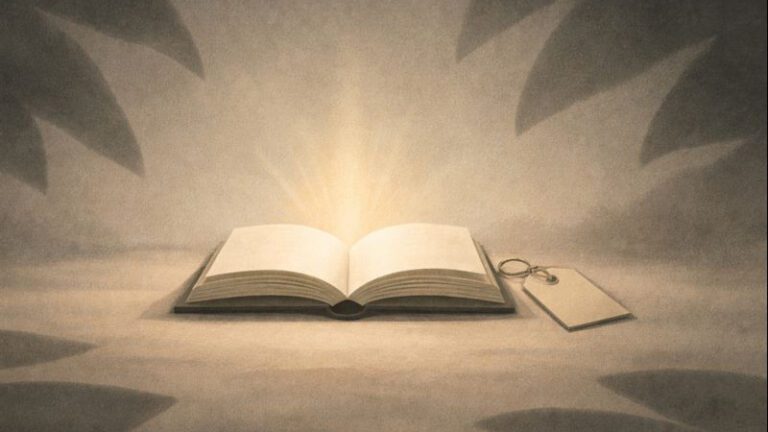Di Indonesia, buku kerap diperlakukan bukan sebagai sumber pengetahuan, melainkan sebagai benda mencurigakan. Ia diawasi, disita, bahkan dijadikan barang bukti, seolah membaca adalah tindakan yang perlu dicurigai.
Ketika saya memasang status foto sedang memegang buku berjudul Muhammad karya Martin Lings—yang juga dikenal dengan nama Abu Bakar Sirajuddin—seorang teman berkomentar, “Wih, piknik isih kober moco-moco.”
Saya memang hobi memamerkan foto sedang membaca buku. Bagi saya, ini salah satu bentuk kampanye literasi: mengenalkan buku kepada khalayak luas. Syukur-syukur, dengan cara itu orang menjadi penasaran dan tertarik membaca. Jika orang memamerkan mobil lalu membuat yang melihatnya iri dan ingin memiliki mobil serupa, jangan-jangan dengan memamerkan buku orang juga terdorong untuk membaca dan memamerkan buku. Dengan begitu, buku menjadi semakin akrab dalam kehidupan orang Indonesia.
Namun, ada gejala lain di Indonesia: ketakutan terhadap buku. Buku dianggap berbahaya karena dinilai dapat menyebarkan pemahaman dan ideologi tertentu. Tidak jarang terdengar kabar pembubaran acara diskusi buku. Ada pula buku yang diambil dari tempat kos dan dijadikan barang bukti bahwa pemiliknya menganut paham tertentu.
Saya ingin membahas persoalan ini. Jika buku diyakini sangat berpengaruh terhadap cara berpikir manusia, seharusnya buku justru dibaca, bukan ditakuti. Jika seseorang tidak menyukai buku dengan aliran tertentu, semestinya ia lebih giat membaca buku-buku yang ia sukai agar pemahamannya semakin kuat. Namun, kenyataannya sering tidak demikian. Banyak pelarang diskusi buku justru tidak menyukai bacaan sama sekali—baik yang sejalan dengan pandangannya, apalagi yang berbeda.
Saya geli melihat buku dijadikan barang bukti atas paham seseorang. Dalam kasus-kasus lain—seperti pencurian, pemerkosaan, korupsi, atau penipuan—saya tidak pernah melihat penyidik melacak buku apa yang dibaca pelakunya. Ketika koruptor tertangkap, mengapa tidak ditanya apa bacaan favoritnya? Faktanya, pembaca kitab suci bisa saja korup, pembaca undang-undang pun bisa korup.
Foto buku yang saya unggah di status WhatsApp itu diambil saat saya berada di rumah makan Mang Engking, Ungaran. Sambil menunggu pesanan datang, saya membaca buku tersebut. Buku ini sudah lama saya beli dan telah saya baca berulang kali. Penulis dan penerjemahnya begitu piawai menyajikan kisah Nabi secara naratif, sehingga saya merasa dekat dengan Nabi saat membacanya. Karena itu, membaca buku ini saya anggap seperti berzikir—sebagaimana teman-teman saya yang menaruh tasbih digital di jarinya untuk mengucap kalimat thayyibah di sela waktu. Saya berzikir dengan cara membaca buku ini di waktu luang.
Apakah membaca buku memang membuat orang cenderung berontak? Membaca buku membuat pikiran hidup, tidak mudah patuh begitu saja. Membaca buku tentang Nabi Muhammad tentu sesuatu yang baik. Tetapi ya, saya memang “berontak”—paling tidak di dalam hati. Selebihnya, saya menggerutu kepada istri atau, lebih jauh, menuliskannya di media sosial, misalnya tentang penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam Sejarah Otentik Nabi Muhammad SAW (Mu’nis, 2018), misalnya, dijelaskan bahwa sistem ekonomi Quraisy pada masa itu bertumpu pada penumpukan kekayaan oleh segelintir elite dan eksploitasi terhadap kelompok lemah. Perdagangan dikuasai keluarga-keluarga kuat, riba dilegalkan. Kehadiran Nabi dengan ajaran barunya mengguncang fondasi ekonomi tersebut karena menggeser orientasi dari keuntungan dan status menuju keadilan dan tanggung jawab sosial.
Ketika saya melihat kondisi Indonesia hari ini—di mana ekonomi dikuasai segelintir orang dan alam dieksploitasi sedemikian rupa—membaca buku itu membuat saya ingin menggugat dan bersuara. Apakah itu salah? Saya kira hal yang sama juga terjadi ketika saya membaca buku tentang Pancasila sebagai dasar negara. Di sana ada nilai ketuhanan, ada pula keadilan sosial. Maka jangan salahkan jika orang kemudian mengkritik, menuliskannya dalam bentuk buku, dan mendiskusikan buku tersebut.